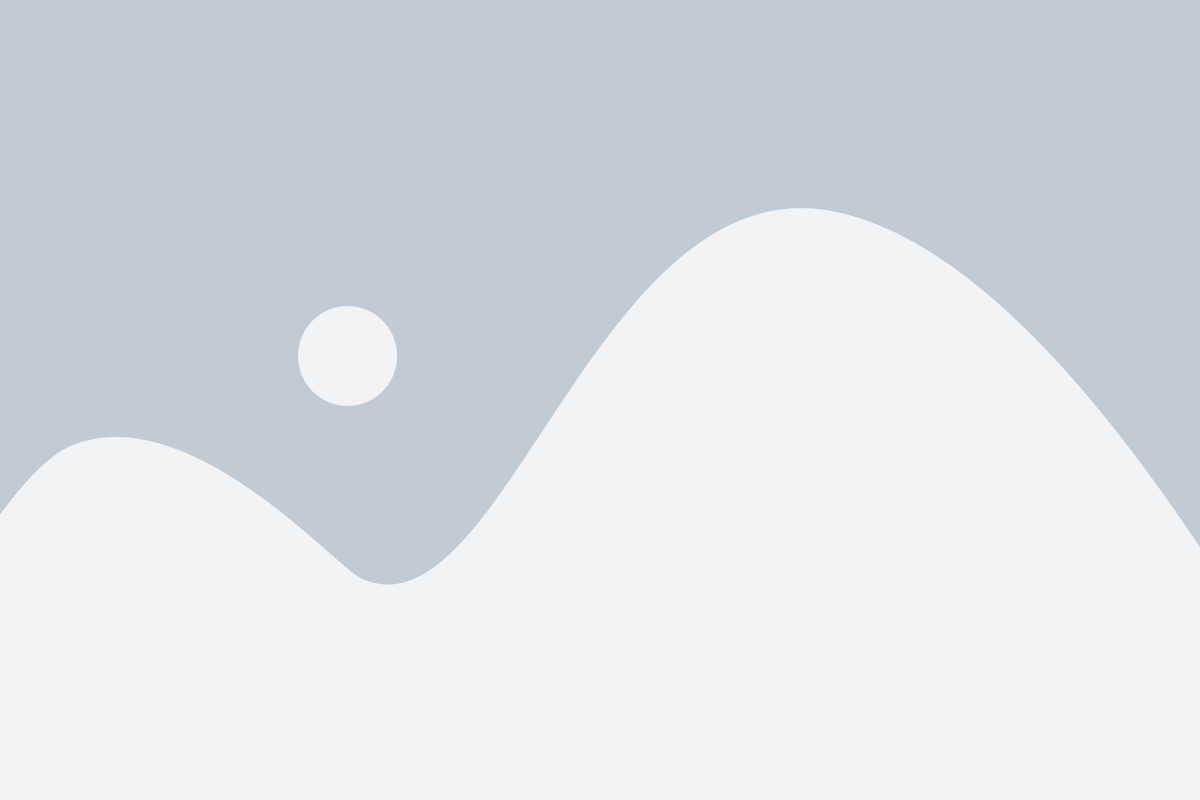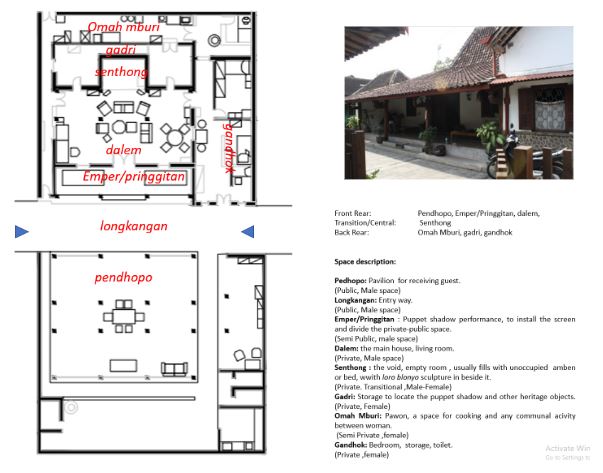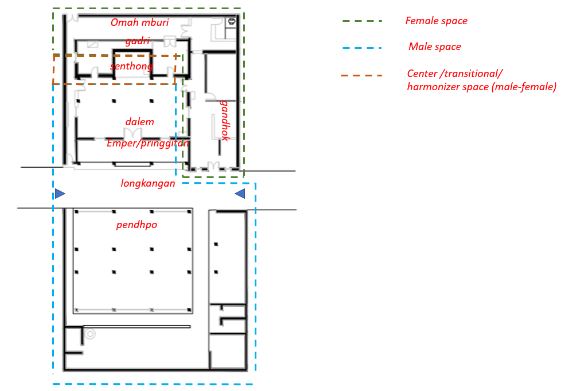“Cuando pueda cocinar ya se puede casar”
“Jika kau bisa memasak, maka kau bisa menikah”
Ibuku, María Eugenia Lizano
Banyak yang bisa dikatakan mengenai masak-memasak dan wanita dalam wilayah yang saat ini dikenal dengan istilah kolonial: “Amerika Latin’. Daerah tersebut dikenal oleh penduduk asli sebagai “Abya Yala” yang berarti “Tanah Subur”.
Namun, sebelum berbicara mengenai masak-memasak dan opresi, mari mulai dari permulaannya: warna kulit.
Sebelum para penjajah spanyol tiba di Abya Yala, setiap orang di benua itu memiliki “kulit sawo matang”. Para penjajah dari spanyol tersebut merupakan orang-orang pertama dengan kulit putih pada keseluruhan wilayah tersebut. Beberapa dekade setelah mereka menetap dan mempelajari budaya, bahasa, serta rute menuju emas, perak, air, dan makanan, mereka mulai menyerang dan menjajah keseluruhan benua.
Mereka menghancurkan tempat-tempat suci; memperbudak perempuan, laki-laki, anak-anak; memaksa pribumi membangun gereja dan memeluk agama Katolik. Mereka mencuri artefak-artefak suci, menculik orang-orang berkulit cokelat, dan menempatkan mereka di kebun binatang manusia. Mereka membawa pelbagai penyakit yang tidak pernah menjangkiti penduduk asli (dus, mereka tidak memiliki kekebalan terhadapnya), hingga mereka meninggal jauh lebih cepat daripada orang-orang yang meninggal karena pandemi COVID-19.
Daerah kolonisasi inggris yang saat ini dikenal sebagai Kanada dan Amerika Serikat (oleh penduduk asli dikenal sebagai “Pulau Penyu”) dan penjajahan spanyol di Abya Yala memiliki dampak yang destruktif bagi penduduk asli. Dalam waktu singkat, cara hidup mereka berubah selamanya. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hilangnya hak atas tanah yang mereka tempati, penyakit, serta pemberlakuan hukum yang melanggar budaya, kedaulatan, dan sistem organisasi mereka.
Para lelaki berkulit putih berusaha mati-matian untuk “membersihkan” ras penduduk asli dan menempatkan diri mereka sebagai pusat kemasyarakatan dan standar kecantikan. Setelah kampanye-kampanye massal genosida dan pemerkosaan sistematis beribu-ribu perempuan penduduk asli berkulit cokelat, anak-anak mereka lahir, dan anak-anak ini mulai memiliki kulit yang semakin dan semakin cerah.
Periode asimilasi pada dasarnya merupakan proses “pemutihan” yang dialami oleh penduduk asli. Memaksa mereka menjadi semakin kehilangan keasliannya dan semakin Eropa. Tidak hanya dengan “menciptakan” anak-anak yang lebih terang kulitnya, tetapi juga dengan memaksa penduduk asli untuk meninggalkan budaya mereka atau didorong ke pinggiran negara kolonial-pendatang eurosentris.
Untuk mematahkan semangat mereka dan hubungan mereka dengan budaya mereka, para pendatang memaksa penduduk asli untuk memotong rambut panjang mereka, mengganti pakaian tradisional mereka dengan pakaian formal Eropa, menghentikan penggunaan tato serta perhiasan tubuh, dan meninggalkan semua penanda budaya yang mengidentifikasi mereka demi asimilasi ke dalam dunia kristen kulit putih.
Inilah alasan mengapa terdapat banyak orang berkulit putih di Pulau Penyu dan Abya Yala, karena penjajah ingin membuat eropa baru di tanah adat pribumi. Orang Eropa tidak memiliki tujuan lain, mereka ingin memusnahkan penduduk asli dan menyebarkan gen mereka dengan segala cara.
Mengapa tidak kita buat-buat ras baru untuk mengelabui penduduk asli agar percaya bahwa mereka bukan penduduk asli lagi karena orang Eropa mengatakan demikian? Dari sini, lahirlah kata “Mestizo”.
“Mestizo” atau “mestiza” berarti “darah campuran”. Ini adalah ras yang diciptakan oleh penjajah yang diperuntukkan bagi setiap orang penduduk asli campuran yang lahir setelah penjajahan di Abya Yala. Mereka begitu terfokus untuk menghapus kepribumian sehingga mereka menciptakan sistem kasta kolonial dengan 16 ras yang berbeda untuk menghapus ras asli. Melalui beberapa jebakan sosial, selama bertahun-tahun, Aymara, Huetar, Bribri, Kuna, Quechua, Cabecar, Telire dan setiap suku mulai berkurang jumlahnya. Orang-orang meninggalkan Nama Suku ini dan mulai menyebut diri mereka “darah campuran”: “Mestizo”, label pertama yang mereka ciptakan setelah menggabungkan orang Eropa dan pribumi.
Penduduk asli dipaksa untuk menyangkal identitas mereka sendiri karena di bawah kekaisaran Spanyol, “darah campuran” akan selalu memiliki lebih banyak hak dan suara dalam masyarakat daripada kelompok pribumi mana pun.
Hal ini berbeda dengan Indonesia. Jiwa saya iri dengan penduduk asli dari sini karena mereka lebih beruntung dalam melestarikan identitas suku mereka: Jawa, Bali, Batak, Sunda, Dayak, dan lainnya yang masih memiliki identitas, tradisi, bahasa, gastronomi, dan kosmologi asli mereka. Di Kosta Rika, tempat keluarga saya berasal, orang-orang Huetar hampir terhapus dari sejarah. Tiada agama yang terlestarikan. Tiada tekstil tradisional. Tiada makanan tradisional. Bahkan bahasa asli pun tidak terlestarikan..
Tapi tidak semuanya hilang, berkat ancestras (leluhur perempuan) kami yang lari dari komunitas-komunitas pribumi ke pegunungan dan lolos dari orang kulit putih. Saat ini masih ada orang dengan kulit sawo matang di setiap negara di Abya Yala dan Pulau Penyu.
Dengan lahirnya Negara, penduduk asli kehilangan haknya. Tanah itu diberi nama baru oleh penjajah, beserta seperangkat aturan sosial-budaya baru yang tidak diketahui sebelumnya. Perempuan sekarang ditakdirkan untuk berada di dapur. Tidak ada kesempatan untuk belajar, untuk memutuskan karir apa yang ingin mereka kejar, atau bahkan waktu untuk diri mereka sendiri.
“Los valores de la familia tradicional” (nilai-nilai keluarga tradisional) memaksakan seperangkat ide, perilaku, dan ekspektasi baru bagi perempuan setelah berpuluh-puluh tahun orang spanyol menguasai setiap aspek kehidupan masyarakat adat.
Perempuan diharapkan hanya untuk beranak. Mereka diharapkan subur. Jika mereka tidak bisa memiliki anak, mereka dianggap sebagai suatu kegagalan. Sudah begitu, jika anak-anak dimanjakan, mereka dianggap ibu yang buruk. Perempuan diharapkan memasak tiga kali sehari untuk keluarga dan membersihkan seluruh bagian rumah sendirian. Jika tidak, mereka dianggap jorok dan tidak bertanggung jawab. Dan tentu saja, seorang perempuan diharapkan melakukan hubungan seks setiap kali suaminya menginginkannya bahkan jika dia tidak berminat untuk itu, dan hal itu tidak akan pernah dianggap pemerkosaan.
Tidak mungkin membicarakan gender dan kelas sosial ekonomi tanpa membicarakan warna kulit. Mayoritas perempuan yang tidak tamat sekolah bekerja di sektor informal, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kelas pekerja secara turun-temurun adalah perempuan berkulit cokelat—bukan perempuan kulit putih dari Kosta Rika. Hal tersebut masih berlangsung hingga kini.
Kolonisasi meletakkan pondasi dasar bagi sistem masyarakat yang memastikan keturunan kulit putih orang Eropa mempertahankan posisi mereka di puncak tangga. Sementara itu, perempuan berkulit coklat yang lahir di negara yang sama, hingga saat ini tidak memiliki status ekonomi yang sama, tidak memiliki kesempatan yang sama, dan menghadapi tantangan dan kekerasan rasial yang lebih besar setiap harinya.
Perempuan berkulit cokelatlah yang memasak untuk perempuan berkulit putih. Perempuan berkulit cokelatlah orang-orang yang tinggal di rumah dan bebersih ketika perempuan berkulit putih ke luar, perempuan berkulit cokelatlah orang-orang yang menghadapi diskriminasi berdasarkan warna kulit, pekerjaan, dan latar belakang mereka.
cukuplah eksklusioner untuk berpikir bahwa perempuanlah yang membersihkan rumah, membesarkan anak-anak, dan memasak sepanjang hari dan setiap hari tak memiliki cara untuk merasa berdaya dan membangun perlawanan dari dapur mereka.
“Ruang sosialisasi di dapur dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh dan memperkuat proses penyembuhan melalui ketahanan. Hal ini memungkinkan untuk mengenali dinamika inter dan intrapersonal yang mendasari terbangunnya persaudarian yang terjadi di dapur, sehingga berhasil menekankan kembali ruang dapur sebagai potensiator proses transformatif subjektivitas pada perempuan” (Almanza Salazar,D. Parra Peña, AM, 2016, hlm.l 3)
Berada di dapur dan menghabiskan waktu bersama selama berjam-jam di sana, memberi perempuan kesempatan untuk meneruskan pengetahuan dari generasi ke generasi, untuk mengembangkan strategi pengendalian, memperkuat ikatan dengan perempuan lain, dan menekankan kembali pengalaman masa lalu, kenyataan saat ini, dan impian-impian mereka.
Meskipun memasak dan berada di dapur bisa menjadi pekerjaan yang memberdayakan bagi sebagian perempuan, penting untuk dipahami dan disadari bahwa ada banyak machismo (sistem penindasan terhadap perempuan) yang mengabaikan perempuan dan pekerjaan mereka.
Masyarakat memberi perempuan peran “Penyelamat”. Seorang wanita penyelamat memahami bahwa semua orang dalam keluarga lebih penting dan didahulukan daripada dirinya sendiri.. Dia dipaksa bekerja sepanjang hari untuk melayani keluarga dan tidak mendapatkan imbalan finansial, melakukan pekerjaan fisik dan emosional yang terus-menerus, dan niscaya, mengalami masalah-masalah kesehatan. Perkataan Abya Yala yang terkenal: “Quitarse el bocado de la boca” (mencicipi dari mulutmu) menggambarkan hal ini dengan baik. Ini mengacu pada kebiasaan yang dimiliki perempuan di mana mereka memutuskan untuk makan makanan apa saja yang tersisakan setelah anak-anak dan suami mereka makan..
Siklus yang melecehkan dan eksploitatif ini mengingatkan para perempuan bahwa setiap kali mereka keluar untuk membeli sayur dan buah, mereka harus segera pulang untuk memasak bagi mereka yang sedang beristirahat, tanpa imbalan sepeserpun, sama sekali diabaikan kecuali saat di mana mereka tidak memenuhi ekspektasi suami dan anak-anak mereka. Di mana dinamika dan dimensi kekuasaan yang berbeda akan mengingatkannya pada inferioritas dirinya dan tanggung jawabnya sebagai pengasuh.
Tidak dapat disangkal bahwa penindasan memang dialami oleh perempuan di dapur, tetapi juga benar bahwa perempuan dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nugini, Abya Yala, dan Pulau Penyu memiliki kemungkinan untuk mengubah ruang ini menjadi kenyataan yang memberdayakan dengan menuntut suami mereka untuk belajar memasak, membagi tugas di dapur, dan memiliki penghasilan sendiri.
inggris/spanyol: Saya menolak penggunaan huruf kapital untuk menandai kebangsaan dari para penjajah.