Cerita ini merupakan susunan sejauh ingatan tentang pengamatan saya ketika menjalani residensi Trans/Voice Project Indonesia-Taiwan selama 4 bulan, dengan metode penelitian etnografi dan fokus pada ekspresi seni Pekerja Migrant Indonesia (PMI) di Taiwan.
Ingatan ini bermula dari cerita seorang kawan bernama Tony Sarwono, PMI asal Yogyakarta, seorang pekerja pabrik. Berawal dari obrolan sederhana di Shelter SPA distrik Zhongli, Taiwan, dari layar hp nya, ia menunjukan lukisannya yang bergaya abstrak. “setengah sadar saya melukis” ucapnya. Ia mengakui moment “katarsis” yang acapkali dirasakan seniman ketika membuat karya. Serupa bisikan dari dalam yang membuatnya dengan enteng melukis setiap guratan garis tebal dengan perpaduan warna yang cenderung muram. Melihat karya dan cerita Tony, lantas membuat Deden Bulqini yang akrab disapa Bul, seniman asal Bandung langsung mengajak Tony berkolaborasi dalam pameran berupa karya video art dan instalasi berjuluk “Ruang: Antara dan Sementara” di Open Contemporary Art Center (OCAC), distrik Datong, Taipei pada 15-16 Juni 2019 silam.
Bul mengungkapkan, bahwa ia tertarik melihat shelter dalam relasinya antara ruang dan tubuh para pekerja migran. Sebagai ruang sementara, Bul melihat shelter sebagai rumah penampungan/ sementara yang berfungsi sebagai persinggahan para PMI yang bermasalah. Rasa penasaran Bul akan hubungan ruang dan tubuh tersebut ia uji coba dalam workshop seni rupa. Hasilnya, berupa empat lukisan tubuh figuratif. Pada tubuh-tubuh lukisan tersebut ditembakan video aktivitas mereka selama di shelter seperti: mengobrol, video call bersama keluarga/pasangan, memancing, hingga kursus bahasa mandarin.
Begitu pun dengan Tony yang melukis teman-teman PMI penghuni shelter. Figur-figur yang kentara dengan ekspresi dan aktivitas hidup keseharian.
“Kita disediakan makan, tempat tidur dan menghibur diri, yah kelihatannya enak tapi sebenarnya pikiran kita ruwet, seperti harapan yang belum jelas” ungkap Tony mewakili perasaan teman-temannya.
Lebih lanjut, ia merasakan keterlibatannya di pameran ini seperti membangkitkan kembali “bisikan dari dalam” tersebut, setelah sekian lama tubuh dan jiwanya menjadi mesin pabrik. “Dengan pameran ini saya merasa jiwa seni saya kembali dan bisa diekspresikan” jelas Tony.

Mengapa PMI berkesenian?
Pada minggu pertama, ketika saya melakukan residensi di Taiwan, saya mengalami kegagapan saat melakukan pengamatan tentang komunitas dan ekspresi seni pekerja migrant. Bekal pengetahuan yang didapatkan dari buku-buku referensi yang saya baca selalu seputar aktivisme PMI dalam memperjuangkan hak pahlawan devisa, tuntutan keadilan buruh pada majikan, juga motivasi mereka menjadi PMI dengan titik berat pada alasan menghidupi dapur dan membayar hutang. Sima Ting Kuan, seorang sahabat Taiwan yang bergelut di dunia pekerja migran sejak lama mengungkapkan bahwa impian PMI itu sederhana “mimpi mereka hanya untuk keluarga”.
Lebih lanjut, masalah pekerja migran di Indonesia erat kaitannya dengan migrasi global. Sejumlah lembaga internasional menetapkan tiga faktor penentu utama yang mendorong migrasi tenaga kerja internasional, yaitu: daya “tarik”, berupa demografi yang berubah dan kebutuhan pasar tenaga kerja di negara-negara dengan pendapatan tinggi. Daya “dorong”, berupa perbedaan gaji dan tekanan kiris di negara berkembang dan miskin. Terakhir, jaringan antar negara berdasarkan keluarga, budaya dan sejarah. (Irianto, 2011:7). Migrasi adalah strategi bertahan hidup mengingat kebanyakan migrasi dilakukan dengan alasan ekonomi. (OSCE, IOM, dan ILO, 2006: 18).
Ekonomi memang dianggap menjadi kebutuhan dasar untuk daya bertahan hidup diri dan keluarganya, namun secara menyeluruh (holistik) sesungguhnya manusia menurut psikolog Abraham Maslow, dalam piramida kebutuhan manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Lebih dari itu, puncak piramida kebutuhan manusia menurut Maslow yakni “kebutuhan akan penghargaan (esteem needs)” dan kebutuhan akan aktualisasi diri (self-actualization needs). Atas landasan pemikiran inilah, saya ingin mengetahui apa yang membuat mereka merasa bahagia
dan mendapat kepuasan hidup? Oleh karena itu saya kira, seni di kalangan PMI Taiwan menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Khususnya secara komunal dalam bentuk komunitas seni.
Posisi para pekerja migran seringkali dianggap minoritas di negara tempat dia bekerja, namun di tahun 2019, terdapat 270.997 pekerja migran asal Indonesia di Taiwan. Jumlah pekerja migran Indonesia bisa disebut mayoritas dibanding dari negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, bila dibandingkan Arab Saudi, Malaysia, Singapura yang menjadi negara tujuan faforit para PMI, Taiwan sendiri, selain Hongkong, lebih terbuka pada aktivisme ekspresi seni PMI dan sastra migran.
Pandangan saya semakin terbuka terhadap aktivitas seni PMI setelah mendapat undangan melihat Festival Seni Budaya HUT-RI 2019 dengan judul acara “Sensasi Kebebasan” pada 18 Agustus 2019 . Lebih menariknya, poster acara ini menggunakan latar gambar abstrak dari Tony Sarwono dengan rentetan pertunjukan seni yang akan dipentaskan dari berbagai komunitas seni PMI dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-74.
Acara ini dimulai sejak pagi berupa parade budaya teman-teman PMI, mereka berjalan dari halaman Taipei Main Station (TMS) menuju National Taiwan Museum. Di halaman Museum, sudah berdiri panggung di mana saya menyaksikan berbagai pertunjukan seni dari mulai tarian tradisional, musik, teater, pencak silat, singo barong Taiwan/reog, peragaan busana nusantara, pembacaan puisi dan sebagainya.
Pada moment inilah, jaringan pergaulan saya dengan teman-teman komunitas seni mulai berkembang. Hampir setiap minggu, tidak hanya mendapatkan undangan untuk menonton seni pertunjukan di tempat lain, tetapi undangan karaoke, makan dan kumpul-kumpul di aula TMS, diskusi, hingga undangan dugem juga dikirim lewat whatsap atau line. Tubuh saya di Taiwan, tapi rasanya masih Indonesia.
Pada acara Festival Seni Budaya Indonesia tersebut, saya semakin mengenal salah seorang PMI yang aktif bergeliat dalam bidang seni lebih dari 9 tahun. Dwi Surwani, akrab disapa Emak adalah pimpinan dari Sanggar Tresno Budoyo. Emak sebagai sutradara, bersama para aktornya mementaskan pertunjukan teater berjudul “Xiao Lei Kondang” adaptasi dari folklore Malin Kundang versi kehidupan PMI. Tidak semata-mata mengadaptasi cerita folklore popular Indonesia, namun emak menyaksikan sendiri di kampungnya tentang keluarga yang ditinggalkan anak, atau orang tua yang meninggalkan anaknya tetapi tidak pernah kembali ke tanah air. “Pesan dari cerita tersebut, jangan melupakan keluarga dan tanah air” tutur emak.
dan mendapat kepuasan hidup? Oleh karena itu saya kira, seni di kalangan PMI Taiwan menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Khususnya secara komunal dalam bentuk komunitas seni.
Posisi para pekerja migran seringkali dianggap minoritas di negara tempat dia bekerja, namun di tahun 2019, terdapat 270.997 pekerja migran asal Indonesia di Taiwan. Jumlah pekerja migran Indonesia bisa disebut mayoritas dibanding dari negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, bila dibandingkan Arab Saudi, Malaysia, Singapura yang menjadi negara tujuan faforit para PMI, Taiwan sendiri, selain Hongkong, lebih terbuka pada aktivisme ekspresi seni PMI dan sastra migran.
Pandangan saya semakin terbuka terhadap aktivitas seni PMI setelah mendapat undangan melihat Festival Seni Budaya HUT-RI 2019 dengan judul acara “Sensasi Kebebasan” pada 18 Agustus 2019 . Lebih menariknya, poster acara ini menggunakan latar gambar abstrak dari Tony Sarwono dengan rentetan pertunjukan seni yang akan dipentaskan dari berbagai komunitas seni PMI dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-74.
Acara ini dimulai sejak pagi berupa parade budaya teman-teman PMI, mereka berjalan dari halaman Taipei Main Station (TMS) menuju National Taiwan Museum. Di halaman Museum, sudah berdiri panggung di mana saya menyaksikan berbagai pertunjukan seni dari mulai tarian tradisional, musik, teater, pencak silat, singo barong Taiwan/reog, peragaan busana nusantara, pembacaan puisi dan sebagainya.
Pada moment inilah, jaringan pergaulan saya dengan teman-teman komunitas seni mulai berkembang. Hampir setiap minggu, tidak hanya mendapatkan undangan untuk menonton seni pertunjukan di tempat lain, tetapi undangan karaoke, makan dan kumpul-kumpul di aula TMS, diskusi, hingga undangan dugem juga dikirim lewat whatsap atau line. Tubuh saya di Taiwan, tapi rasanya masih Indonesia.
Pada acara Festival Seni Budaya Indonesia tersebut, saya semakin mengenal salah seorang PMI yang aktif bergeliat dalam bidang seni lebih dari 9 tahun. Dwi Surwani, akrab disapa Emak adalah pimpinan dari Sanggar Tresno Budoyo. Emak sebagai sutradara, bersama para aktornya mementaskan pertunjukan teater berjudul “Xiao Lei Kondang” adaptasi dari folklore Malin Kundang versi kehidupan PMI. Tidak semata-mata mengadaptasi cerita folklore popular Indonesia, namun emak menyaksikan sendiri di kampungnya tentang keluarga yang ditinggalkan anak, atau orang tua yang meninggalkan anaknya tetapi tidak pernah kembali ke tanah air. “Pesan dari cerita tersebut, jangan melupakan keluarga dan tanah air” tutur emak.

Dalam obrolan saat makan bersama, ia mengungkapkan bahwa alasan utama mendirikan Tresno Budoyo yaitu “meluangkan jiwa seni”. Acapkali, pekerjaanya sebagai Asisten Rumah Tangga mewajibkannya bekerja 24 jam di rumah majikan. Ketika waktunya libur, emak datang ke TMS membawa koper besar, isinya kostum dan makanan. Untuk pertunjukan “Xiao Lei Kondang:, ia dan para aktor yang berbeda kota berlatih di taman. Sulitnya menentukan jadwal kumpul latihan, menjadi kendala banyak komunitas seni PMI.
Serupa dengan sanggar Tresno Budoyo, komunitas seni reog “Singo Barong Taiwan” memiliki kendala serupa, selain masalah regenerasi. Satu bulan sebelum Singo Barong Taiwan pentas di Pingtung, pada akhir Juni 2019, saya berkesempatan mengunjungi tempat latihan mereka di Toko Indo Cen Cen daerah Zhongli, Taiwan.
Pada saat itu para personil sedang berlatih, di lantai paling atas Toko Indo Cen Cen, sembari menunggu hujan reda, para personil terlihat duduk melingkar dan asik berbincang dalam bahasa Jawa. Sedangkan yang lain, Lorena dan Dinda, dua penari jatilan sedang asik berdandan dan bersiap memakai kostum.
“Kami sudah lama menyewa tempat ini buat kumpul dan simpan kostum, tapi kalau untuk latihan biasanya di taman saat minggu ketiga di setiap bulannya” ungkap Heri, salah seorang pengurus Singo Barong Taiwan.
Dua topeng kepala Singo Barong berhias bulu merak terlihat gagah menghiasi dinding ruangan tersebut. Bukan perkara mudah membawa kedua topeng ke Taiwan. Topeng pertama didatangkan pada tahun 2014 ketika tahun pertama Paguyuban Singo berdiri. Selanjutnya, pada tahun 2018 topeng kedua menyusul didatangkan. Dibutuhkan biaya hingga 1 juta dolar Taiwan, atau sekitar Rp
500 juta untuk mendatangkan topeng Singo Barong tersebut. Darimanakah biayanya? Heri dengan tegas mengungkapkan, biaya tersebut murni dari bantuan teman-teman Pekerja Migran Indonesia.
Memasuki generasi ketiga dan tahun kelima berdirinya Singo Barong Taiwan. Paguyuban ini telah pentas keliling di beberapa kota seperti Hsinchu dan berkali-kali di Taipei. Kehadiran mereka selalu dinanti teman-teman PMI dan animo ketertarikan masyarakat Taiwan pada seni budaya Indonesia juga cukup besar. Namun, hingga saat ini, kendala yang dialami kelompok berada pada soal dana dan regenerasi pemain. “Kalau kita yang nonton banyak. Yang main susah”

Obrolan saya dengan Tresno Budoyo dan Singo Barong Taiwan—bersama komunitas seni lain—mengungkapkan permasalahan utama yang dialami komunitas seni pekerja migran, yang bila dirangkum —dengan keterbatasan jumlah halaman di tulisan ini —di antaranya: masalah regenerasi anggota/pemain, keberlanjutan (sustainable) komunitas setelah ditinggal anggota yang habis kontrak kerja, sekaligus keberlanjutan pekerja seni setelah mereka pulang ke Indonesia. Ruang dan waktu latihan yang sulit karena pekerjaan, penonton (audience) yang notabene masih diminati orang Indonesia. Manajemen dan support keuangan dan tenaga, terakhir adalah stereotype pekerja seni dengan label pekerja migran.
Setelah saya mengetahui berbagai permasalahan tersebut, saya kembali pada pertanyaan dasar: mengapa, mereka —Komunitas seni PMI— dengan susah payah tetap berkesenian, mengapa seni menjadi penting? Sebagian besar mereka menjawab lugas, bahwa: seni itu ekspresi, seni itu hiburan, seni itu identitas.
Ingatan tentang pertunjukan-pertunjukan teater, tari, singo barong, hingga karaoke di warung Indonesia yang saya saksikan dan alami bersama mereka selama residensi ini sepertinya menegaskan itu semua. Seni itu memang penting bukan karena mereka sebagai PMI saja, tapi mereka adalah manusia yang memerlukan nilai aktualisasi, hiburan, katarsis dan identitas budaya.
Ikhtisar
Setelah pulang dari Taiwan, saya bersama teman-teman dari Trans/Voice dan Sunday Screen Bandung, mengunjungi Desa Cihonje, kecamatan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Desa Cihonje merupakan salah satu Desa Migran Produktif di mana sekitar 70% warganya pernah menjadi PMI. Dari cerita Yulia, salah satu mantan PMI di Hongkong dam Macau yang saat ini aktif di Rumah Pintar Cihonje. Dahulu, desa ini memiliki potensi cengkeh sebagai sumber daya alam hingga pada masa Orde Baru, cengkeh sebagai penghasilan utama warganya dikapitalisasi. Konon ceritanya oleh salah satu anak presiden di masa Orde Baru.
Alhasil, ketika sumber daya alam ludes yang tersisa adalah sumber daya manusia yang merantau nasib ke luar negeri. Awalnya, orang tua mereka bekerja ke Arab Saudi dan Malaysia. Beberapa tahun terakhir, Taiwan dan Hongkong menjadi sasaran utama perantauan.
Rumah-rumah tembok di Cihonje dengan warna-warna cerah, para warga yang sebagian besar dapat berbahasa mandarin dan arab. Juga pertemuan kami dengan belasan calon PMI berkemeja putih yang mengikuti pelatihan ke Taiwan. Segala ingatan peristiwa saat di Taiwan dan Cihonje menyadarkan saya bila kebutuhan ekpresi seni dan dapur yang mengepul, seperti dua sisi mata uang, tidak terpisahkan. Semoga arsip ingatan saya di tulisan ini, tidak hanya sekedar cerita. Lebih dari itu, saya tidak bisa mewakili seutuhnya kisah pekerja migran karena PMI juga adalah seutuhnya manusia. Yang ingin berkesenian, juga membahagiakan keluarga.
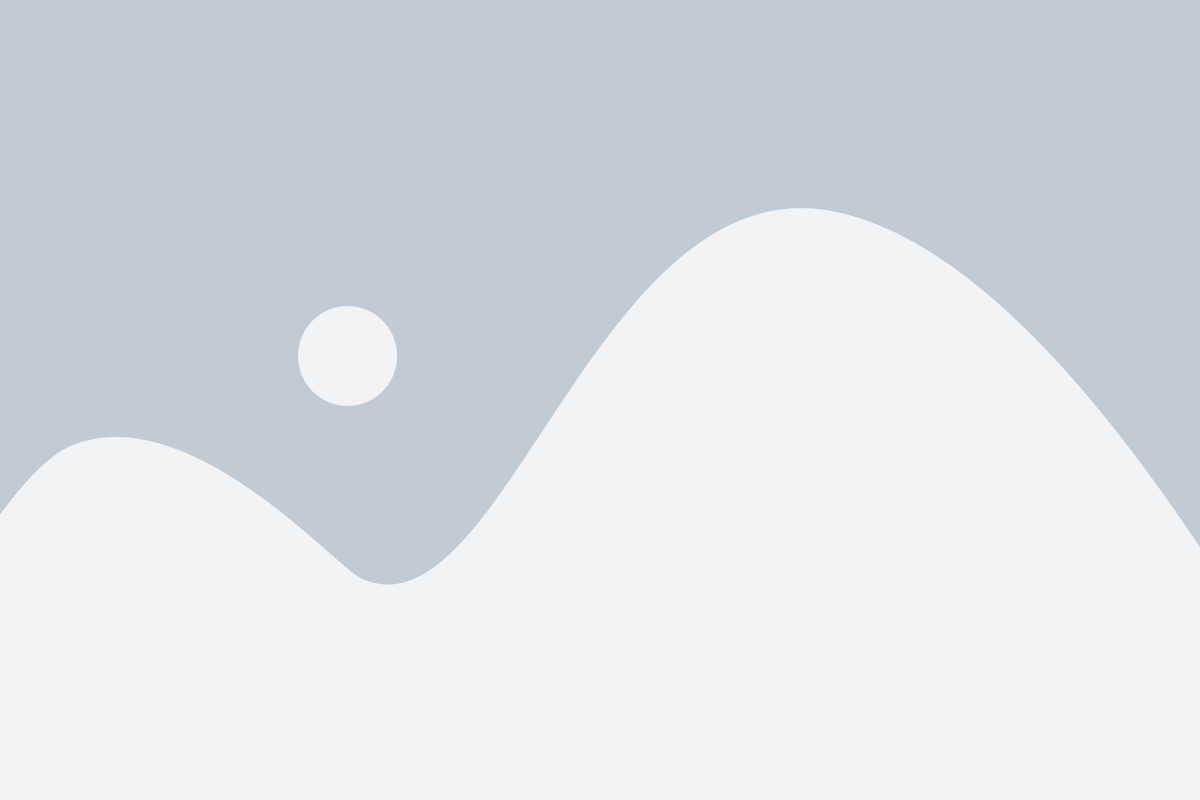
Selvie Agnesia
seorang penulis, dan pekerja seni asal Bandung yang pernah lama menetap di Jakarta. Lulusan Magister Antropologi, Universitas Indonesia. Pada tahun 2019 mengikuti Residensi Trans Voice/Project Indonesia-Taiwan untuk pengamatan komunitas seni dari Pekerja Migrant Indonesia. Hasil pengamatannya dipresentasikan di National Taiwan Museum dan Brillian Times (2019) dll. Ia juga pernah mengikuti residensi untuk Pegiat Budaya di Selandia Baru (2017). Manager Produksi TeaterStudio Indonesia di Festival Tokyo 2012 & 2013 dll. Beberapa tulisannya dimuat di Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos dan berbagai media cetak dan online di Indonesia.
